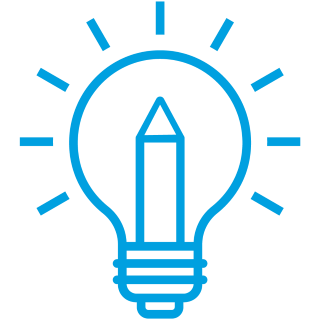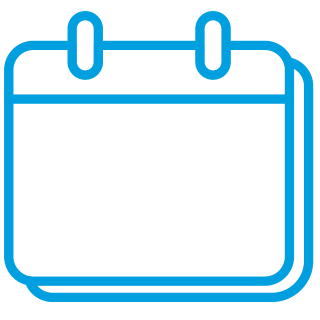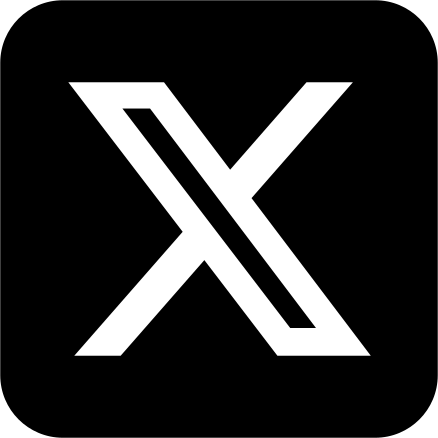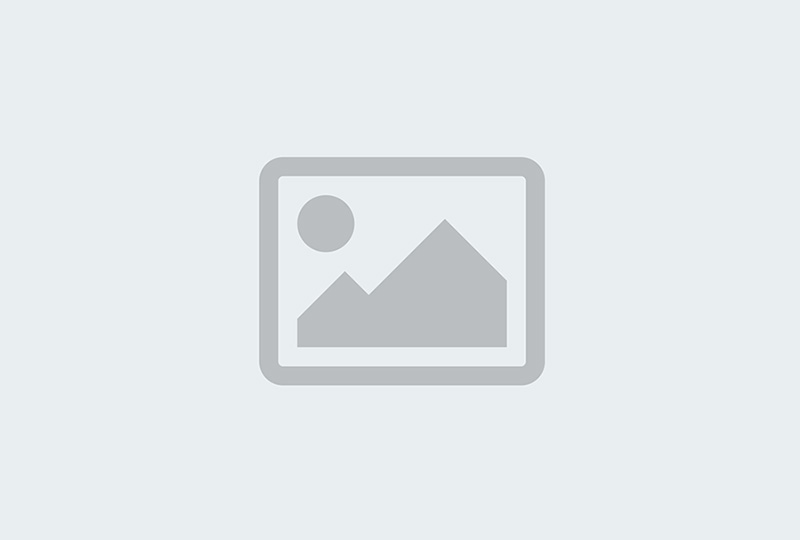Akhir 2020 adalah masa terketar-ketir dalam mengurus keuangan. Pendapatan menurun, dana darurat menipis, berbagai proyek tertunda—yang mana berakhir batal.
Saat otak lagi mencari berbagai strategi agar setidaknya bertahan dalam enam bulan ke depan, saya dihubungi seorang kawan lama.
"Mas brooo! Apa kabar?"
Sapaan berganti obrolan seputar kenangan saat masa kuliah di Bandung, sampai puja-puji beberapa karya saya secara bertubi-tubi hingga saya suuzan: ada perlu apa nih?
Habis, bertahun-tahun sebelumnya gak pernah sapa-sapa atau sekadar kasih apresiasi. Paling-paling cuma lihat selewat di linimasa media sosial. Dan itu bukan masalah bagi saya.
Ah, pikiran buruk itu menyebalkan ya! Lebih menyebalkan lagi saat pikiran buruk itu... benar adanya!
"Jadi gini, bro, kira-kira bisa pinjem duit gak ya, seadanya bro saja, gue bakal berusaha kembalikan secepatnya."
"Wah, elo lagi sakit? Atau ada keluarga yang lagi dirawat?"
Sempat hening sekian detik, diselipkan hela napas yang membuat saya waswas, semakin membayangkan segala skenario buruk yang berkenaan dengan COVID-19.
"...untuk keperluan bulanan."
Jawabannya menyentak iman, mengingat segala posting-annya penuh dengan kemewahan ala ibu kota.
Baca juga: Mengatur Uang: Refleksi Diri dan Perjalanan Pribadi
Dia adalah tipikal apa pun barang yang sedang dibicarakan, maka itulah konten media sosial yang senantiasa ditampilkan. Mulai dari antre beli gadget setara biaya bulanan saya di Ubud, sampai kumpul mingguan mengayuh sepeda senilai 12 kali sepeda motor saya.
Tentu saja, saya penasaran berbuah nyinyir. Kok bisa-bisanya selama ini punya gaya hidup mewah ala ibu kota, tapi sampai perlu menghubungi warga desa buat bantuan keperluan bulanan? Hush!
Singkat cerita, via berbagai buah bibir, akhirnya saya jadi tau kalau sang teman lama terjebak pinjol—pinjaman online. Awalnya terkendali, tapi saat virus menyerang, duit bulanan tinggal kenangan.
Rupanya buat sebagian orang, mengaku susah adalah kekalahan. Alhasil, menjaga kemewahan terasa mengharuskan. Terlena segala kebutuhan tersier.
Saya sendiri bukan tipikal orang yang akan mencicil kebutuhan tersier, tapi... apa sih sebenarnya kebutuhan tersier? Menurut saya, kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Sayangnya, semakin hari kebutuhan mewah semakin terasa relatif.
Baca juga: Pondasi Keuangan dari Ruang-Ruang Masa Kecil
Sepeda ratusan juta buat saya termasuk tersier, tapi buat teman saya bisa jadi (terasa) primer. Membina pergaulan gowes buatnya lebih dari sekedar mengayuh sepeda bersama, tapi bisa jadi kegiatan melobi proyek.
Lalu saya jadi teringat diri sendiri saat awal-awal tinggal di ibu kota, enam belas tahun lalu. Saat itu, ada beberapa kegiatan nongkrong selepas kerja yang jadi kebutuhan primer. Padahal habis kerja bisa langsung balik sih.
Tetapi, berkat rangkaian nongkrong bareng itu, jadi dapat banyak jalan menuju kerja sampingan, untuk mengganti biaya nongkrong yang semalamnya bisa menghabiskan jatah makan siang rumahan dua mingguan! Yah, dulu perlu taktik sih buat kegiatan nongkrong ini. Contohnya, saya sering skip sarapan atau makan siang demi bisa terlihat bersahaja saat nongkrong malam.
Lalu… beda zaman, beda kebutuhan. Memasuki era 2010-an, jalan-jalan (traveling) terasa sebagai kewajiban. Rasanya nelangsa banget kalau melihat konten media sosial tanpa konten traveling.
Seakan tujuan akhir kehidupan saya adalah berkaryawisata ke berbagai benua, sampai-sampai saya khilaf meniadakan kebutuhan yang lebih pokok: dana darurat. Saat itu kerjaan dan proyek lagi bejibun, jadi tak perlu waswas duit habis!
Baca juga: Mengapa Setiap Orang Harus Memiliki Dana Darurat
Siklus sombong ini berakhir saat saya sakit parah. Parahnya itu sampai gak bisa kerja sampai kurang lebih setahun berikutnya. Bahkan, saya perlu tiga tahun untuk bisa kembali kerja maksimal. Alhasil, proyek-proyek digagalkan, pemasukan tak ada, dan saya terpaksa meminta pertolongan pada para sahabat.
Uh, ujung-ujungnya gak jauh beda ya sama teman bergaya mewah ibu kota tadi? Sama-sama keliru memilih prioritas kebutuhan primer. Rasanya seakan-akan ditertawakan rangkaian posting-an yang tampak tak perlu pikir panjang untuk menghabiskan uang.
Mau tak mau, pemahaman akan kebutuhan pokok kembali ke dasar: sandang, pangan, dan papan yang membantu masa pemulihan. Begitu pula dengan tabungan. Saat kembali berpenghasilan, saya menerapkan hal ini: bila ada sisa setelah memenuhi kebutuhan primer, maka uang masuk ke tabungan dana darurat.
Maka kali ini patokan merasa kaya raya bukan hanya di Saldo Aktif, tapi di fitur deposito berjangka andalan saya di Jenius: Maxi Saver—apakah nominalnya sudah bisa jadi dana darurat selama setahun?
Kalau sudah terlampaui, bolehlah kelebihan berikutnya dipakai buat memanjakan diri dengan berbagai kebutuhan tersier. Karena sesungguhnya, ada kemewahan yang tak pernah saya sesali: nonton konser band favorit di beda benua.
Yang paling terkenang indah sejauh ini adalah pengalaman nonton konser U2 di Inglewood, pinggiran kota Los Angeles. Selain nyanyi bareng lagu-lagu di album The Joshua Tree yang ikut membentuk kenangan manis masa kecil, di arena konser saya bertemu para pesohor internasional dari LL Cool J, Lionel Richie, sampai John Mayer. Selebritas dunia jadi terasa inner circle, haha!
Duh, gak sabar kembali beredar!
Baca juga: Kelas Itu Bernama Perjalanan
Tetapi ya harap tabah dulu saja. Karena tampaknya pandemi juga mereka ulang kebutuhan dasar secara global. Wisata mancanegara, kongko-kongko, dan segala kegiatan komunal, kini malah berpotensi jadi perusak kebahagiaan. Sehat walafiat dan waras bukan lagi sekadar ada, tapi kenikmatan yang sungguh primer.
Jadi, jika sampai saat ini pertemanan diam-diam membuatmu merasa wajib menyicil kemewahan agar bisa lebih diterima, TINGGALKAN!
Artikel ini ditulis oleh Vabyo, teman Jenius yang merupakan seorang penulis lepas yang saat ini tinggal di Bali. Cek artikel dari guest writer-guest writer lain pada laman Jenius Blog.
Ilustrasi pada artikel ini merupakan karya Sukutangan, teman Jenius yang merupakan freelance illustrator di Bali.